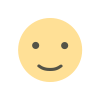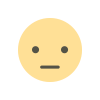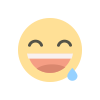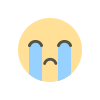Brangkali Kepala Kita akan Meledak
Catatan untuk lakon-lakon Aktor Amatir karya AB. Asmarandana

Kekacauan ada di mana-mana, di dalam pikiran, di atas kapal, di dalam struktur kalimat, di dalam bus, di penjual asongan dan dagangannya, tidak ketinggalan tokoh-tokohnya. Membaca Lakon Amatir karya AB. Asmarandana membuat kita terkoneksi dengan gagasan-gagasan absurd. Ada semacam pertaruhan yang mengerikan, memaksa kepala pembaca atau penonton meringsek ke dalam sebuah ruang yang sempit sekali di sana kita harus meledakkan sesuatu, atau justru kepala kitalah yang buntu dan meledak.
Kita diperhadapkan pada banyak dialog janggal, bahkan fatal. Ada tokoh yang mengaku sudah tujuh kali ke kamar mandi tapi tidak bisa pipis, tokoh yang kerjaannya memandikan ikan setiap pagi dan mengajarkan burung untuk tenggelam, dan juga tokoh yang sering memainkan sandiwara cinta tetapi tidak pernah jatuh cinta. Kehidupan macam apa yan ditampilkan di sini? Adegan diaraknya mayat sutradara yang disyukuri oleh seorang ustaz juga tidak kalah absurdnya.
Tidak hanya banyak membentangkan saling-silang absurditas dalam dialog tokoh-tokoh aneh, tetapi yang “lebih gila” adalah para aktor. Dengan stabilitas energinya yang ditunjukan dengan kalimat-kalimat yang susul menyusul, melawan, memanipulasi dan akhirnya membentangkan persoalan persoalan yang pelik. Darinya muncul perspektif, retorika, dalih, pertanyaan, yang tampak secara koheren membangun waktu yang terasa berjalan berat.
Saya membayangkan lakon ini ditulis di tengah kondisi psikis penulisnya sedang berkecamuk. Semua penulis adalah penggelisah, tetapi ada yang sedikit lebih menonjol daripada soal itu, terutama pada bagian yang sifatnya eksperimentatif: pelompatan adegan dan dialog yang ekstrim. Ada semacam ketidakpuasan. Setidaknya ada belenggu yang hendak dilonggarkan untuk sekadar melihat apakah di depan ada kemungkinan-kemungkinan? Kelak itu muncul di bagian akhir.
Membaca dialog yang susul-menyusul dengan beban-beban simbol absurditas mengingatkan kita pada mimpi-mimpi yang sering dialami oleh kebayankan orang – katakanlah misalnya kita yang bermimpi mengendarai sebuah kapal tetapi yang kita lewati justru gunung yang tinggi. Tetapi kita tetap menjalani mimpi itu sambil tetap berusaha melihat apa yang seharusnya kita lihat meski tidak masuk akal (absurd) dan melampaui yang riil.
Relevan mengkaitkan mimpi dengan karya sastra (lakon), sebab bahan dasarnya adalah imajinasi. Dalam ranah psikologi Freud menyatakan pemenuhan keinginan adalah alamat dari setiap mimpi. Dan setiap tindakan dari aktor-aktor tentu dipicu oleh keinginan. Apa misi mereka?
Kita bisa bertanya mengapa orang-orang di atas panggung itu berlaku aneh demikian? Lajos Egri, dalam rangka menelusuri tindakan atau lakuan aktor menyatakan “tidak ada satu laku pun di dunia ini yang asal mula dan hasilnya adalah satu. Segala sesuatu dihasilkan dari sesuatu yang lain; laku tidak dapat berasal dari dirinya sendiri.”
Pertanyaan trsebut di atas bisa kita telusuri pada bagian akhir lakon ini, pada percakapan sebelum narasi penutupnya. Problem terbesar aktor-aktor amatir yang hidup di atas panggung adalah kematian, Kematian, atau “kematian”. Atau barangkali menuju kematian. Jika benar mati berarti kalah – setidaknya dua kata itu terasosiasi, maka Chairil Anwar juga benar telah mendaku hidup hanya menunda kekalahan. Sepesimis itukah penyair eksistensialis itu tentang hidup?
Menurut aturan dan perlu untuk mengetahui apakah hidup ini mempunyai arti? Albert Camus bertanya demikian. Untuk menjawab pertanyaannya itu, Camus sendiri bergolak dengan pemikiran yang serius hingga ia tiba pada persoalan bunuh diri. Sekali pun seseorang tidak mempercayai Tuhan, kata pemikir itu, bunuh diri tidak boleh terjadi. Alih-alih menyelesaika tragedi, lakon ini justru barangkali melampaui tragedy. Konstruksi narasi naskah ini mengarah ke membunuh diri. Tetapi saya bisa saja salah dalam hal ini. Satu hal yang pasti secara tersurat cirinya mengarah ke sana: sebenarnya hidup atau matikah yang lebih berharga?
Kalimat terakhir dari lakon itu sebernarnya sudah klasik. Sering sekali dipertanyakan oleh banyak filsuf. Tetapi saking menariknya, ada banyak sekali anasir yang bisa timbul dari sana. Tiada kan habis waktu untuk menarik pertanyaan itu ke berbagai konteks ruang dan waktu. Pertanyaan itu sendiri tidak terjawab, meski sebenarnya dialog terakhir aktornya secara naif dialamatkan pada Tuhan.
Lakon ini membentangkan simpang jalan pilihan. Jika sepasang suami istri di ruang tengah (rumah?) menyerahkan pelik persoalan pada Tuhan (apakah penulis hendak bilang manusia tidak berdaya?) maka lakon ini justru ditutup dengan sebuah petanyaan mana yang lebih penting hidup atau mati?
Asmarandana sepertinya hendak mengingatkan kita semua, bahwa sebelum sampai ke Tuhan hidup ini harus kita selesaikan kini di sini, meski sendiri. Jika tidak, barangkali kepala kita akan meledak seperti yang disiratkan dialog filosofis dalam lakon ini: diam berarti mati, mati diam-diam.[]
Samarinda, 20 November 2021
oleh Dahri Dahlan, akademisi FIBUNMUL Samarinda.
Sumber rujukan
Egri, Lajos. 2020. The Art of Dramatic Writing. Kalabuku: Yogyakarta.
Freud, Sigmund. 2020. The Interpretation of Dreams (edisi terjemahan). Indoliterasi: Yogyakarta.
Soekito, Wiratmo. 2020. Albert Camus bagian II dalam Drama Berakhir dengan Diskusi. DKJ: Jakarta.
What's Your Reaction?