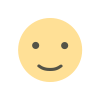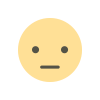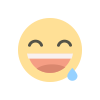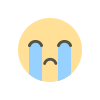Naik Kelas Adalah Hak Asasi Manusia

INILAHTASIK.COM | Di sebuah negeri demokratis nan beradab, di mana rakyat bebas memilih presiden setiap lima tahun dan bebas mengunggah video TikTok setiap lima menit, ada satu prinsip suci yang tak boleh diganggu gugat: naik kelas adalah hak asasi manusia. Tak peduli apakah anak bisa membaca atau tidak, yang penting ia bahagia, sehat, dan tidak tertekan.
Karena siapa kita yang berani menekan anak-anak bangsa dengan deretan abjad dan angka-angka rumit seperti 7²×8⅔? Kita hidup di zaman yang tidak lagi percaya pada “kemampuan”, tapi “niat baik”. Dan selama siswa itu niat baik datang ke sekolah, meski hanya duduk memandangi jendela atau bermain gasing digital di bawah meja, itu cukup membuktikan bahwa dia pantas naik kelas.
Kurikulum Kasih Sayang
Pendidikan hari ini telah berevolusi. Dahulu ada murid dimarahi karena tak hafal perkalian. Sekarang, guru bisa dimarahi karena membuat anak menangis. Dahulu nilai merah adalah tanda bahwa kita harus belajar lebih giat. Sekarang, nilai merah dianggap sebagai pelanggaran hak anak untuk merasa bangga. Maka diciptakanlah kurikulum yang lebih manusiawi: tidak lagi berdasarkan pencapaian, tapi perasaan.
Tak bisa baca? Tak apa. Anak punya bakat lain—katanya seninya tinggi, walau belum pernah ikut pentas. Tak bisa menulis? Tak masalah. Dunia sekarang sudah serba audio-visual. Toh nanti kerja juga tinggal pakai voice note atau tinggal tanya meta ai
Dan ketika seorang anak kelas 5 SD belum bisa membaca soal ujian, guru hanya bisa menatap langit dan berkata, “Ini bukan salah dia, ini salah sistem.” Sementara sistem berkata, “Bukan salah saya, ini karena tekanan psikologis keluarga.” Dan keluarga menjawab, “Kami tidak ingin anak kami merasa gagal.” Maka, solusi terbaiknya adalah: naikkan saja.
Murid Jadi Raja
Dulu, guru digugu dan ditiru. Sekarang, guru bisa dilaporkan dan dihukum disuruh mundur lagi.. Ada guru yang menegur siswa tak mengerjakan PR, besoknya viral. Ada guru yang memberi tugas tambahan, dicap melanggar prinsip keseimbangan emosional anak. Maka guru pun belajar, bukan untuk mengajar lebih baik, tapi untuk lebih pandai memilih kata agar tidak disalahpahami.
Murid adalah raja. Dan seperti di kerajaan-kerajaan besar, raja tidak boleh dikecewakan. Maka jangan heran jika hari ini banyak guru menilai dengan perasaan. Soal tak dijawab? Setidaknya anak menulis nama. Nilai: 60. Jawaban ngawur? Yang penting berani mencoba. Nilai: 75. Tak hadir ujian? Ya sudah, toh absensi bukan indikator kecerdasan. Nilai: tetap naik.
Administrasi Adalah Segalanya
Hal yang paling pasti dalam dunia pendidikan kita adalah ini: lebih penting laporan daripada proses. Anak-anak mungkin tidak bisa baca, tapi sekolah bisa menyusun dokumen 40 halaman untuk membuktikan bahwa proses belajar mengajar berjalan “dengan semangat literasi”.
Birokrasi pendidikan hari ini begitu kompleks dan kreatif, hingga kadang kita lupa bahwa inti sekolah adalah belajar. Dinas meminta bukti kegiatan. Guru sibuk memotret siswa menggambar huruf "A" (yang dibantu oleh wali kelas). Semua tampak produktif. Semua terlihat bahagia. Semua tampak berhasil.
Dan saat siswa naik kelas meski belum bisa membaca, kepala sekolah tersenyum puas: “Lihat, angka partisipasi meningkat. Angka tinggal kelas menurun drastis.” Sebuah keberhasilan luar biasa, kecuali satu hal kecil: anak-anak itu masih buta huruf.
Panggung Sandiwara Pendidikan
Sistem pendidikan kita kini lebih mirip pertunjukan kolosal. Semua aktor sudah siap: guru, orang tua, pejabat dinas, dan tentu saja murid sebagai pemeran utama. Skripnya sudah ditentukan: semua harus naik kelas, semua harus bahagia. Tak penting isi kepala, yang penting isi rapor.
Dan seperti kata seorang dalang masa kini yang frustasi melihat Dorna mati terlalu awal: "Cerita sudah tidak menarik lagi."
Mungkin memang sudah waktunya kita akui: ini bukan lagi pendidikan, ini pertunjukan besar. Dan seperti pertunjukan lainnya, tak masalah jika penonton tertawa karena absurditas. Asal semua pemain naik panggung... dan naik kelas.
What's Your Reaction?