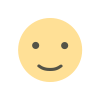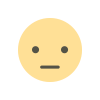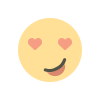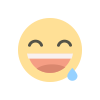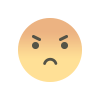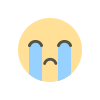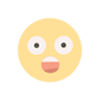Nisan Bagi Sandiwara, Tafsir Filosofis atas Kematian Teater di Tengah Zaman Edan

And action...
Tulisan ini berangkat dari kematian tokoh Resi Dorna dalam pewayangan yang terlalu cepat sebagai metafora lenyapnya peran antagonis dalam narasi budaya kita. Dengan pendekatan reflektif-filosofis, esai ini memeriksa bagaimana dunia kontemporer yang diwarnai hegemoni ormas, aparat, dan birokrasi seni telah membungkam suara teater sebagai ruang kritik dan kontemplasi. Disertai rujukan terhadap Serat Kalatidha karya Ranggawarsita, tulisan ini menjadi renungan atas lenyapnya nalar dan seni di tengah zaman yang digerakkan oleh politik identitas, kekerasan simbolik, dan pasar pertunjukan yang banal.
Adegan pertama : Dorna Mati Terlalu Awal
Semalam suntuk kita menonton wayang, dan tiba-tiba Dorna mati. Bukan karena takdir lakon, tapi karena dalang dipaksa mempercepat cerita. Sang guru Kurawa itu, yang sering jadi biang tipu, biang licik, biang kecurangan, biang kerok, dihabisi sebelum waktunya. “Biar penonton cepat pulang,” kata satu suara. “Terlalu rumit ceritanya,” kata yang lain. Tapi, saat Dorna mati, lakon kehilangan kedalaman. Yang tersisa hanyalah gerak tanpa makna, adegan tanpa penafsiran.
Dalam dunia modern, Dorna adalah simbol. Ia mewakili ambiguitas moral, kecerdikan yang membingungkan, dan ironi yang membentuk realitas. Dengan matinya Dorna terlalu dini, dunia kehilangan antagonis yang sesungguhnya dibutuhkan agar kita bisa membedakan cahaya dari bayang-bayang. Ketika antagonis tak lagi hadir, dunia menjadi datar. Dan cerita kehilangan daya pikatnya.
Adegan dua ; Ormas, Aparat, dan Daur Kekuasaan yang Membungkam
Hari ini, bukan hanya Dorna yang mati. Teater sebagai ruang tanding gagasan juga sekarat. Panggung-panggung rakyat, yang dulu hidup di balai desa dan serambi masjid, kini dibungkam oleh suara toa dan pengeras dari ormas yang mengklaim diri sebagai penjaga moralitas. Ironisnya, moral yang mereka jaga lebih sering berwujud larangan daripada pertimbangan. Pentas seni dibubarkan karena dianggap mengandung penyimpangan budaya. Para aktor dituduh mempromosikan nilai-nilai Barat, padahal yang mereka tampilkan adalah cermin dari kondisi lokal yang absurd.
Aparat, alih-alih melindungi ruang kreatif, justru sering menjadi perpanjangan tangan dari tekanan massa. Dengan dalih menjaga ketertiban, mereka menyegel ekspresi. Di bawah bendera “izin keramaian” dan “keamanan”, aparat mengatur naskah tanpa pernah membaca teksnya. Dunia menjadi kelir tanpa dalang, lakon tanpa ruh. Sebagaimana ditulis Tuan Ranggawarsita
Ngengingi jamane kaliyuga,
Seta dadi puspita,
Duryudana katon kawicaksanane....
(Manakala dunia memasuki zaman kaliyuga,
Iblis tampil seperti bunga,
Duryodana terlihat seperti orang bijak.)
Seni, yang seharusnya menjadi ruang pembacaan terhadap kekacauan sosial, justru dianggap pembuat kekacauan itu sendiri. Yang dibela bukan nilai, tapi citra. Yang dijaga bukan masyarakat, tapi rasa nyaman mereka yang berkuasa.
Adegan 3
Birokrasi Seni: Ketika Proposal Lebih Penting dari Pertunjukan
Di sisi lain, birokrasi seni menjelma jadi labirin absurd. Dana hibah untuk pertunjukan rakyat disyaratkan melalui proposal formal, laporan keuangan yang kompleks, dan bentuk pertunjukan yang “menarik secara visual” namun aman secara politis. Aktor dituntut membuat RAB sebelum memahami roh naskah. Sutradara diminta membuat "outcome terukur" untuk adegan yang justru diciptakan dari ketidakterukuran emosi, huh hah kita diciptakan untuk jahat lewat kebaikan
Seni akhirnya terperangkap dalam budaya kertas dan presentasi. Yang dihitung bukan lagi pengaruh batin penonton, tapi jumlah audiens, capaian tayangan di media sosial, dan feedback dari pejabat dinas. Teater tak lagi bicara tentang tubuh dan kesadaran, melainkan tentang nilai ekonomis dan keberlanjutan program. Maka jangan heran jika banyak panggung hari ini hanya menjadi bayang-bayang dari brosur promosi.
Kita sedang hidup dalam dunia yang menertawakan teater, bukan karena isinya lucu, tapi karena teater sudah tak mampu lagi membalas tawa dengan tanya. Dalam istilah Ranggawarsita, kita hidup dalam zaman “tanpa tuan dan tanpa aturan.” Zaman edan, di mana hanya mereka yang ikut edan yang bisa hidup.
Epilog: Nisan dan Kemungkinan Baru
Mungkin sudah waktunya kita buatkan nisan bagi teater. Tapi bukan nisan sebagai akhir. Melainkan sebagai tanda bahwa seni sejati tak lahir dari panggung yang diterangi lampu sorot, melainkan dari kegelisahan yang tak muat dalam laporan pertanggungjawaban. Kita butuh teater yang lahir dari luka dan tanya. Teater yang tidak butuh izin untuk jujur. Teater yang tidak dipoles agar laku, tapi dibakar agar menyala.
Sebagaimana lagi lagi Ranggawarsita menulis, dalam sunyi zaman edan, kita hanya bisa berdoa:
“Lamun angkara murka kalawan rubeda wus kadulu,
Sing sapa linuwih ing ngaurip,
Samudana lan sabar anggoning laku.”
(Bila angkara dan malapetaka sudah tampak jelas,
Siapa pun yang ingin selamat dalam hidupnya,
Harus berani bersabar dan memaafkan dalam tiap langkahnya.)
Dalam sabar dan sabda itulah, mungkin kita bisa kembali membangkitkan teater. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai napas. Sebagai gugatan terhadap dunia yang terlalu banyak bermain sandiwara, hingga lupa bahwa sandiwara sejati pernah ada—dan kini terbaring sunyi, menanti kita menziarahinya.
What's Your Reaction?